[Ruang Karya] Cerpen: Aku Bukan Malaikat
Aku Bukan Malaikat
(Cr:Google)
Penulis: Farah Allifa Humaida
Seorang gadis kecil melangkah tertatih dengan langkah berat, ia tampak kelelahan setelah berjalan tanpa mengenal waktu untuk menjajakan jajanannya demi sesuap nasi dan lauk untuk keluarganya dalam beberapa hari ke depan. Di hadapannya, seorang ibu yang terlihat lelah dan pucat menyambutnya di depan sebuah pekarangan rumah.
Aku mengamati interaksi gadis itu dengan ibunya, mendengar bisikan lelah dari mulut kecilnya yang mengadu akan kurangnya perhatian orang- orang berdompet tebal saat melihat dirinya berjualan. Aku mendekati gadis itu, mengambil beberapa bungkus lotek dalam mika yang ia jajakan dan menyodorkan uang dua kali lipat dari yang diharapkan gadis itu.
Gadis itu menatapku bingung. Ia mempertanyakan kewarasanku, kemudian mengucapkan sepatah kata yang membuatku ingin tertawa.
“Terima kasih, malaikat.” Suara kecil yang polos dan bahagia berdering di telingaku.
Aku memicingkan mata pada ibunya yang syok saat berhasil mengenaliku. Dia menarik
lengan gadis itu menjauh dariku.
“Sama- sama, tapi aku bukan malaikat.” Aku tersenyum meninggalkan gadis itu yang bersikeras menolak ajakan ibunya untuk segera masuk ke dalam rumah.
Potongan buah dan sambal.
***
Saat itu, pagi pertama aku membawa langkahku menginjak tanah asing. Lumpur perlahan menempel di sepatuku, memberiku peringatan akan ketimpangan kawasan asing ini dengan kawasan yang biasa aku tinggali. Kutatap rumah- rumah dengan pekarangan berlumpur itu satu persatu, anehnya meski dengan mata telanjang, aku bisa mengenali sampah yang tersembunyi di bawah lumpur, berbagai buah yang jatuh penyebab bau busuk disekitar pohon, dan banjir yang konon mencintai kawasan ini. Timbullah sekelibat pertanyaan dalam batinku.
“Di manakah letaknya kebijaksanaan di kawasan ini? Apakah ada pengetahuan di
sini?”
Tanpa membiarkan waktu merenggut langkah dan niatku, kusegerakan diriku berbincang dengan warga sekitar, menemui pemimpin dan pengawas terdekat dengan niat membantu dengan ikhlas.
“Oh, anda mau membersihkan dan bantu- bantu daerah sini? Boleh sih, silakan saja.”
Hatiku merasa tenang, seolah mendapat dukungan. Ku coba utarakan niatku mencari tempat tinggal sementara untuk memudahkan tujuanku mengubah kawasan ini dengan campur tangan langsung dari kedua tanganku.
“Hm, tempat tinggal ya. Kok susah ya, ada sih, tapi kecil.”
“Iya, tidak apa- apa pak, karena saya memang niat membantu.” Ucapku ringan.
Dibawalah aku menuju gubuk kecil di pinggir kebun buah dengan aroma buah busuk
yang seolah ingin membunuhku.
“Duh, sial, tapi aku harus sabar” Batinku berteriak.
***
Hari demi hari pun berlalu. Kuburan sampah yang sebelumnya tersembunyi di bawah lumpur perlahan-lahan menghilang. Pohon buah yang dahulu bau busuk buahnya menyengat hidung pun kini tiada. Aku telah mengalihfungsikan semuanya menjadi bahan untuk kerajinan serta berjualan.
Tanpa terasa, sudah sebulan penuh aku berada di sana. Kawasan itu berubah menjadi tempat yang bersih dan rapi. Penduduknya semakin Makmur, hasil kerajinan sampah dijual dengan harga yang lebih baik, hasil kebun mereka diolah menjadi komoditas yang bernilai jual.
Malam itu, seperti malam-malam biasanya, aku membuka laptop dan ponsel. Mencatat progres harianku. Saat hendak mengambil air putih di sebelah kanan laptop kesayanganku, gelas itu terguling dan airnya menyiram lenganku. Saat itulah aku sadar.
“Ada yang aneh”
Ku tatap lenganku, yang dulunya mulus dan bersih, kini penuh luka dan bekas. Aku terdiam. Ada sesuatu yang salah.
“Kenapa bisa begini?” tanyaku dalam hati. Aku menepis pemikiran itu perlahan sambil berusaha tetap bertahan di hantaman kantuk yang menyelimutiku. Malam itu aku berniat untuk bekerja lebih keras, karena esoknya aku bisa pulang, kembali ke pelukan hangat keluargaku setelah setelah mencapai salah satu visiku, menjadi agen perubahan.
Menjelang pagi, peristiwa tidak nyaman melandaku. Suhu tubuhku mendadak naik. Aku menggigil, tapi di sisi lain tubuhku seperti terbakar. Aku mencoba memikirkan siapa yang bisa kuhubungi. Bukankah para penduduk biasanya menolongku, menjulurkan tangan dan menawarkan bantuan?
Ku coba hubungi mereka yang terdekat dengan penuh harap. Kesadaran perlahan
menghilang dari diriku.
“Kemana semua orang pergi? Kenapa tak ada yang bisa kuhubungi?”
Aku hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhku seolah tenggelam dalam lamunan pedih yang tak berujung.
Aku mendengar detak jam tangan kesayanganku, perlahan, tapi terus-menerus, memenuhi telingaku. Suara-suara pun bermunculan, suara mereka yang berterima kasih
kepadaku:
“Terima kasih, Kakak Malaikat.”
“Terima kasih, Malaikat.”
“Kamu memang malaikat...”
Namun malam itu, entah kenapa ucapan itu tidak terasa seperti pujian, tapi justru menjadi hunusan tajam di dada. Bukan lagi melodi indah, melainkan melodi yang rusak dan menyayat hati. Ada yang salah.
“Apa yang salah?” gumamku.
Perlahan-lahan, sinar matahari mulai menyentuh tubuhku. Aku mencoba membuka mata, walau kelopaknya terasa sangat berat. Terdengar keributan di luar. Samar- samar, aku mendengar dan mengenali suara orang-orang yang dulu menyematkan “malaikat” sebagai nama panggilanku.
Sayup-sayup, kudengar percakapan:
“Bagaimana kalau dia mati?”
“Sepertinya sih, dia memang bakal mati.”
“Kenapa kamu bisa yakin?”
“Mana ada malaikat datang ke tempat seperti ini, membuat perubahan besar, lalu tiba-tiba lenyap. Dia pasti manusia. Dia pasti bakal mati sebentar lagi, karena itu dia beramal sekuat tenaga.”
“Lalu kita tinggal tunggu dia mati. Setelah itu kita bisa ambil laptop dan ponselnya, oh, dompetnya sepertinya tebal.”
“Pemakamannya?”
“Pemakaman apa? Bawa saja ke rumah sakit. Rumah sakit pasti mau merawatnya. Kita gak usah mikirin biaya pemakaman. Bilang saja dia cuma pengunjung Kawasan ini.”
“Bagus, kita bisa memanfaatkan pengorbanannya sebaik mungkin. Kuakui kalau malaikat yang satu ini sangat hebat dan membantu”
Aku merasa keringat dingin muncul di punggungku. Di dalam hati kecilku, aku berteriak dan mengerang gelisah.
“Gila. Mereka gila.”
Bisa-bisanya mereka berpikir aku datang hanya untuk mati. Bisa-bisanya mereka dengan sangat berlebihan menyamakanku sebagai ‘malaikat’ yang hanya bisa berbuat baik. Kepalaku terasa berat dan sakit. Sekali lagi, kesadaran menghilang dari benakku.
***
Keesokan harinya, aku merasa tubuhku diangkat oleh beberapa orang menuju mobil. Terdengar sirine ambulan yang tidak ada orang yang tidak mengenalinya saat mendengarnya. Ambulan itu berhenti. Samar-samar aku mencium bau disinfektan, bau yang kukenal baik. Aku ditinggalkan di IGD, sendirian.
“Kenapa kamu?” Muncul suara yang telah lama tidak kudengar. Kupaksakan senyum dan membuka mata sedikit.
“Saya nggak enak badan...”
“Sudah hubungi orang tuamu?”
Untunglah, rumah sakit itu biasa dikunjungi keluargaku. Dokter kenalanku segera menghubungi mereka. Akhirnya, kehangatan keluargaku menyirami jiwaku yang nyaris layu.
***
Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kawasan itu karena penasaran, dan untuk mendapatkan kembali beberapa barang berhargaku. Kawasan itu... kini lebih buruk dari sebelumnya. Sampah kembali menumpuk. Lumpur dan bau busuk menyelimuti lagi.
Aku melihat beberapa warga perlahan menghampiriku, memohon agar aku memperbaiki keadaan seperti dulu. Dengan hati yang terluka, aku mengangguk, menyunggingkan senyum “malaikat” andalanku, yang selama ini selalu kutampakkan di depan mereka.
Tapi aku tidak bodoh.
Sudah cukup luka-luka ini menjadi teman setiaku. Pada akhirnya aku membantu mereka, ya, karena aku ‘malaikat’. Tapi kali ini, aku takkan lagi mengorbankan ragaku. Aku beri mereka perintah dan arahan, sementara diriku menikmati laporan sambil bersantai di dalam kost.
Terjadi sesuatu yang tidak kuduga. Mereka ternyata buta. Mereka tak tahu arah. Mereka bahkan tak tahu cara bekerja.
Mau tak mau, aku pun tersadar.
“Inikah yang mengganjal di hatiku?
Di mana mereka saat aku bekerja membersihkan, memperbaiki, dan menata kawasan itu?
Bukankah dulu mereka menawarkan bantuan untukku?
Tunggu.
Bukankah seharusnya mulut yang menawarkan bantuan itu adalah mulutku?” Aku tercengang.
“Astaga” gumamku.
***
Hari-hari kembali berlalu. Tapi kawasan itu tak kunjung membaik. Sampah kembali terkubur lumpur. Banjir menggenangi jalanan. Buah-buahan kembali membusuk.
Warga-warga itu kini datang padaku dengan wajah memerah penuh amarah:
“Kamu bukan malaikat yang dulu!” Bentak salah seorang dari mereka
“Kamu iblis! Pergi! Kami tak butuh kamu!”
Aku tersenyum sinis.
“Tentu saja aku akan pergi.” Bisikku.
Dengan tenang, aku mengambil kembali laptop dan ponselku yang nyaris mereka gadaikan.
Kini, aku diusir oleh mereka yang dulu ku bantu, mereka yang memanggilku malaikat, mereka yang lupa kalau aku juga manusia, sama seperti mereka.
***
Tak lama, kabar itu datang. Kawasan itu hancur. Lebih rusak dari sebelumnya. Banjir di mana-mana. Sampah jadi topping dari genangan lumpurnya. Bau busuk buah-buahan lebih menyengat dari sebelumnya.
Dan di manakah aku saat itu?
Aku pulang.
Ke rumah yang harum oleh cinta dan kehangatan. Ke pangkuan ibu, ke pelukan ayah yang tak menuntut imbalan.
Dalam tujuanku menjadi manusia seutuhnya, kini aku tahu,
Manusia tetaplah manusia
Sebutan malaikat yang di sematkan kepada manusia itu memang indah
Namun juga berbahaya
Mereka yang berhenti menyebutku sebagai malaikat, yah, mereka benar
Aku hanya akan menjadi manusia,
Yang memilih mencintai mereka yang membalas dengan kasih
***
Begitulah serpihan kisahku, di mana terkadang angan membawaku menuju harapan akan kesempurnaan, dimana di dalamnya terdapat pula rasa sayang dan belas kasihan, padahal aku hanyalah manusia yang tak luput dari kekurangan, kesalahan, dan dosa.
Ngomong- ngomong, aku penasaran, bagaimana dengan serpihan kisah milikmu? Apakah kamu malaikat?
Editor: Difa Septiari Dinarsih


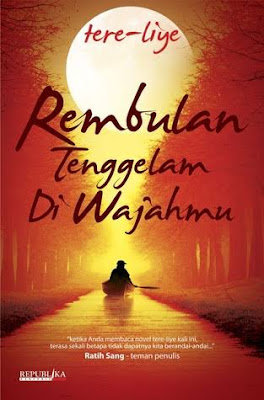
Komentar
Posting Komentar