[Ruang Karya] Resensi Buku: Ronggeng Dukuh Paruk
RUANG KARYA
RESENSI BUKU
Judul : Ronggeng Dukuh Paruk
Penulis : Ahmad Tohari
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Tahun Terbit : 1982
Tebal Buku : 520 Halaman
Genre : Fiksi Sejarah
Penikmat sastra Indonesia tentunya tidak asing dengan Ronggeng Dukuh Paruk, sebuah novel monumental karya Ahmad Tohari. Bukan hanya bercerita tentang tradisi ronggeng, ia menyingkap sebuah sejarah kelam tentang seorang perempuan yang menjadi korban dari sistem politik.
Sinopsis
Cerita Ronggeng Dukuh Paruk menggambarkan kehidupan pedesaan yang sarat tradisi, mistisisme, dan kemiskinan, dengan latar di Dukuh Paruk, sebuah desa terpencil yang dihuni tak lebih dari 70 orang. Penduduknya bergantung pada kepercayaan leluhur, Ki Secamenggala, yang diyakini sebagai pendiri desa sekaligus pusat kiblat kebatinan.
Ditengah kepercayaan itu, Srintil, gadis yatim piatu berusia 11 tahun, diyakini sebagai titisan Indang Ronggeng oleh kakeknya, Sakarya—seorang kamitua Dukuh Paruk yang percaya roh Ki Secamenggala telah mengutus cucunya untuk menghidupkan kembali martabat desa.
Dengan dorongan masyarakat dan bantuan dukun ronggeng, Kartareja dan isitrinya, Srintil pun dilatih untuk menjadi penari ronggeng yang akan menghidupkan kembali semangat Dukuh Paruk setelah belasan tahun tanpa ronggeng.
Sebelum resmi menjadi Ronggeng, Srintil harus menjalani serangkaian ritual, termasuk prosesi sayembara “bukak klambu” — tradisi yang melelang keperawanannya kepada pria dengan tawaran tertinggi. Transaksi tubuh perempuan atas nama adat dan kebanggaan desa.
Sebelum ritual dilangsungkan, Srintil yang diam-diam juga mencintai teman kecilnya, Rasus, memaksanya untuk menjadi orang pertama yang megambil keperawanannya sebagai bentuk pemberontakan kecil terhadap takdir yang dipaksakan.
Setelah srintil resmi menjadi ronggeng, Rasus tidak dapat menerima kenyataan bahwa Srintil menjadi perempuan milik publik. Rasus memutuskan untuk keluar dari pedukuhan, hingga takdir membawanya menjadi seorang tentara.
Seketika kehidupan Srintil berubah. Ia menjadi ronggeng terkenal yang dielu-elukan masyarakat dan menjadi perempuan pemuas para lelaki dari rakyat biasa hingga kalangan pejabat. Disisi lain, Rasus menjalani hidup baru di lingkungan militer, menjauh dari desa dan cinta lamanya.
Konflik mencapai puncaknya ketika situasi politik 1965 mulai memengaruhi kehidupan di Dukuh Paruk. Tanpa sepenuhnya menyadari konsekuensinya, Srintil dan para pengiringnya dijadikan alat untuk menarik massa dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kelompok komunis.
Awalnya, Sakarya sebagai kamitua menyadari sasmita yang disampaikan alam, bahwa akan terjadi malapetakan besar di Pedukuhan itu, tetapi mereka tak bisa menghentikan ketelibatannya karena terbebani hutang budi pada salah satu anggota komunis penyelenggara rapat. Akibatnya, mereka dicap sebagai simpatisan dan ditangkap sebagai tahanan politik (tapol). Sementara itu, Dukuh Paruk hancur, terpuruk dalam ketakutan dan kehancuran akibat gejolak politik yang tak mereka pahami.
Di tengah penderitaan dan penyesalan yang dialami, Srintil mulai mempertanyakan hidupnya. Kekayaan dan ketenaran tidak mampu mengisi kehampaan batinnya. Ia menginginkan kehidupan yang sederhana: menjadi istri, menjadi ibu, menjadi perempuan “somahan”. Namun, masyarakat, adat, dan masa lalu kelam terus membelenggunya. Hingga semuanya terlambat, ketika Rasus telah kembali ke pedukuhan kecil itu, Srintil sudah kehilangan dirinya dan kewarasannya.
Kelebihan buku
Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menjadikannya dapat dinikmati oleh pembaca umum tanpa kehilangan kedalaman makna. Narasinya mengalir tenang dan reflektif, menyisipkan banyak pesan moral penting—mulai dari isu hak atas tubuh perempuan, dampak psikologis dari trauma, hingga pentingnya pendidikan dan kesadaran kolektif. Alurnya sederhana, namun kuat dalam menyampaikan absurditas sistem politik yang bisa menuding sebuah desa terpencil yang terlibat komunis. Kisah ini juga membangkitkan kesadaran sejarah bahwa tragedi masa lalu tidak boleh dilupakan agar tidak kembali terulang.
Kekurangan buku
Novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Penjabaran suasana desa yang terlalu detail justru membuat ritme cerita terasa lambat dan bertele-tele, serta penggunaan bahasa daerah tanpa terjemahan yang berpotensi membingungkan pembaca dari luar Jawa. Selain itu, penggunaan kata-kata kasar dan eksplisit dalam beberapa bagian, menjadikannya kurang cocok sebagai bahan bacaan edukatif tanpa pendampingan. Meski begitu, kekurangan-kekurangan ini tidak mengurangi kekuatan utama novel dalam menyuarakan pergulatan batin, sosial, dan politik yang membelenggu masyarakat kecil.
Kesimpulan
Ronggeng Dukuh Paruk menjadi cerminan kompleksitas relasi antara adat, tubuh perempuan, kemiskinan, dan politik. Melalui narasi yang sederhana namun menyentuh, buku ini berhasil menyajikan kritik sosial yang tajam tanpa kehilangan keindahan sastra. Meskipun memiliki beberapa kelemahan dari segi alur dan gaya penulisan, novel ini tetap relevan dibaca sebagai refleksi sejarah dan potret masyarakat kecil yang sering kali luput dari perhatian. Yang membuat novel ini wajib dibaca adalah kemampuannya menyatukan kisah personal dan politik secara halus namun menggugah. Novel ini tak hanya menawarkan cerita yang menyentuh, tapi juga mengajak pembaca memahami sisi gelap sejarah Indonesia—tanpa menggurui.
Editor: Tsabita Maula Izzati


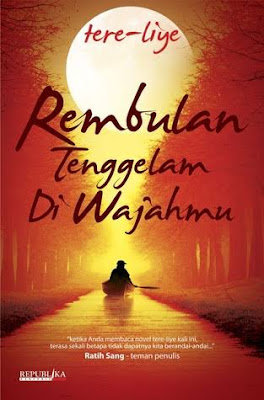
Komentar
Posting Komentar