[Ruang Karya] Cerpen: "Darah di Tanah yang Dijajah"
Darah masih mengalir di antara pahaku saat aku berjongkok di sudut kamar sempit ini. Aroma kemenyan bercampur keringat lelaki asing masih melekat di kulitku. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang sudah kering bersama sisa-sisa harga diri yang direnggut sejak pertama kali kaki mereka menginjak tanah ini.
Namaku Sari. Seorang perempuan pribumi yang terlahir di tanah yang subur, namun tumbuh di bawah bayang-bayang penindasan. Aku pernah bermimpi menjadi perajin kain batik seperti ibuku, menyulam pola-pola yang indah di atas selembar kain. Namun, takdir membawaku ke tempat ini-menjadi alat pemuas nafsu pejabat-pejabat asing yang menganggap tubuhku tak lebih dari hiburan semalam.
Mereka datang dengan senjata dan hukum yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menyebutnya peradaban, tapi bagi kami, itu belenggu. Sejak Belanda menguasai tanah ini, kami perempuan pribumi tidak lebih dari barang dagangan. Jika bukan menjadi budak di ladang, kami dijual untuk memenuhi kesenangan para tuan besar. Mereka menyebut kami nyai, seolah memberi kehormatan, padahal kami hanya boneka yang bisa mereka buang kapan saja.
Aku masih ingat hari pertama aku dipaksa masuk ke rumah ini. Ibuku menangis, meratap, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ayahku? Ia sudah lama mati, dihantam popor senapan saat mencoba mempertahankan sawah kecil kami dari tangan-tangan serakah. Aku hanya bisa menggigit lidah saat tangan kasar menyeretku masuk ke dalam ruangan gelap, di mana aroma anggur dan keringat bercampur menjadi satu.
"Jangan melawan, Sari," bisik seorang perempuan tua yang lebih dulu terperangkap di sini. "Melawan hanya akan membuatmu mati lebih cepat."
Tapi apakah ini bisa disebut hidup?
Setiap malam, aku dipaksa tersenyum, menyajikan tubuhku seperti hidangan di atas meja. Mereka menilai kami dari warna kulit, dari lekuk tubuh. "Ah, Sari, kau harus lebih putih kalau ingin mendapatkan tuan yang lebih baik," kata salah satu nyai yang lebih lama di sini. Maka dipaksalah aku merendam tubuh dengan air jeruk nipis setiap sore, berharap warna kulit sawo matangku akan memudar. Tapi aku tahu, seberapa pun aku berusaha, aku tetap bukan bagian dari dunia mereka.
Malam ini, aku kembali dipanggil. Seorang pejabat tinggi, katanya. Orang yang berkuasa menentukan hidup dan matiku. Aku berjalan dengan langkah kecil, menahan gemetar di seluruh tubuh. Aku sudah terbiasa, tapi rasa takut tak pernah benar-benar hilang.
Saat pintu terbuka, aku melihatnya. Seorang pria tua dengan mata biru yang tajam. Ia menatapku seperti seorang kolektor yang menilai barang dagangannya. Aku ingin lari, ingin terteriak, ingin membakar rumah ini beserta seluruh penghuninya. Tapi aku hanya bisa berdiri kaku, membiarkan tangannya meraih daguku.
"Cantik," katanya dalam bahasa yang tak benar-benar kupahami. "Tapi bisa lebih cantik jika kau lebih putih."
Aku menggigit bibir. Kata-kata itu mengiris lebih dalam daripada cakaran perempuan-perempuan yang saling berebut tempat di sini. Aku tidak cukup putih. Tidak cukup langsing.
Tidak cukup tinggi. Tidak cukup-Tidak cukup untuk dihargai sebagai manusia.
Dalam sekejap, aku merasa ingin melawan. Tapi aku tahu, aku sendirian. Di luar sana, penjajahan masih berlangsung. Laki-laki kami dibunuh, perempuan kami dipaksa tunduk. Aku adalah satu dari sekian banyak korban yang kisahnya tak akan pernah tercatat dalam buku sejarah. Kami hanya bayang-bayang, luka yang tak terlihat.
Namun, malam ini aku bersumpah. Jika aku tak bisa melawan dengan senjata, aku akan melawan dengan ingatan. Aku akan mengingat setiap derita ini. Suatu hari nanti, saat tanah ini kembali menjadi milik kami, akan ada perempuan-perempuan lain yang berani berbicara. Yang akan menuntut keadilan atas tubuh-tubuh yang direnggut. Dan meskipun aku mungkin tak akan pernah keluar dari rumah ini hidup-hidup, setidaknya aku tahu bahwa aku pernah ada.
Pagi datang dengan cahaya yang terasa menyakitkan di mataku. Aku mendengar suara langkah-langkah berat mendekat. Para prajurit datang membawa perintah baru. Salah satu nyai berbisik kepadaku, "Ada rencana pemberontakan di kota. Para lelaki akan menyerang kediaman mereka."
Aku menelan ludah. Haruskah aku berharap?
Sore itu, suara tembakan menggema di kejauhan. Aku melongok dari jendela kecil di kamarku. Asap hitam mengepul, pertanda bahwa perlawanan benar-benar terjadi. Aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya-harapan.
Malam itu, saat lelaki bermata biru itu datang lagi, aku tidak lagi gemetar. Aku menatapnya lurus, tidak sebagai budak, tapi sebagai perempuan yang memiliki kemarahan. Ia terkesiap, terkejut melihat sorot mataku yang berbeda.
Aku mungkin tidak memiliki senjata, tapi aku memiliki keberanian. Jika aku harus mati malam ini, setidaknya aku mati dengan kepala tegak.
Lelaki bermata biru itu melangkah mendekat, matanya menelisik wajahku, seakan mencari sesuatu yang telah berubah. Aku tidak menunduk. Aku tidak gemetar. Aku hanya berdiri tegak, menunggu apa yang akan ia lakukan.
"Apa yang terjadi padamu?" suaranya lebih lembut dari biasanya, tapi aku tidak terpancing.
Aku tetap diam. Di luar, suara perlawanan masih menggema. Aku tidak tahu siapa yang menang, tetapi aku tahu aku tidak bisa lagi menjadi perempuan yang pasrah.
Tiba-tiba, pintu di belakangnya terbuka dengan kasar. Seorang prajurit bergegas masuk, wajahnya penuh peluh. "Tuan, para pemberontak telah menerobos gerbang utama. Kita harus pergi sekarang!"
Lelaki bermata biru itu mendengus pelan, lalu menoleh kepadaku. "Kau akan tetap di sini," katanya, sebelum berbalik dan mengikuti prajurit itu keluar.
Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku merapat ke pintu, mengintip ke luar. Para penjaga panik, berlari ke sana kemari. Aku tahu aku harus pergi sekarang, atau selamanya tetap terkurung di tempat ini.
Tanpa berpikir panjang, aku menyelinap keluar, menyusuri lorong gelap yang berbau tanah lembap. Jantungku berdegup kencang, tapi langkahku tetap mantap. Aku harus menemukan jalan keluar, aku harus menemukan mereka yang berjuang.
Saat aku hampir mencapai halaman belakang, sebuah tangan kuat mencengkeram lenganku. Aku tersentak, menahan napas. Tapi saat aku menoleh, aku melihat wajah yang kukenal-Nyai yang tadi berbisik padaku.
"Ayo," katanya pelan. "Kita akan melawan bersama."
Aku mengangguk tanpa ragu. Nyai menarik tanganku, membawaku menyusuri lorong sempit yang hanya diterangi cahaya obor dari kejauhan. Suara benturan senjata dan teriakan semakin dekat, menandakan bahwa pertempuran tengah berkecamuk di halaman utama.
"Kita harus melewati dapur, ada pintu rahasia di sana," bisik Nyai sambil terus melangkah cepat. Aku mengikuti langkahnya, menahan napas setiap kali bayangan para penjaga melintas di persimpangan lorong.
Begitu sampai di dapur, Nyai membuka sebuah papan kayu di lantai, memperlihatkan tangga sempit yang mengarah ke bawah. "Masuklah," katanya.
Aku menuruni tangga dengan hati-hati, diikuti Nyai yang menutup kembali papan kayu di atas kami. Terowongan bawah tanah itu lembap dan pengap, tetapi aku tidak mengeluh. Ini adalah satu-satunya jalan keluar.
Kami berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki kami yang terdengar. Setelah beberapa menit, Nyai berhenti di depan sebuah dinding batu dan menekan salah satu batanya. Dinding itu bergeser, memperlihatkan celah yang cukup untuk kami lewati.
Begitu keluar, udara malam menyergap kulitku, membawa aroma asap dan tanah basah. Aku melihat ke sekeliling-kami berada di hutan di belakang benteng. Namun, belum sempat aku bernapas lega, suara derap langkah terdengar dari kejauhan.
"Mereka mengejar kita," ucap Nyai pelan. "Ayo cepat!"
Kami berlari menembus pepohonan, ranting-ranting kecil mencambuk kulitku, tetapi aku tidak peduli. Aku harus bertahan. Aku harus menemukan mereka yang berjuang.
Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di depan kami. Aku berhenti mendadak, hampir jatuh ke belakang. Lelaki itu berdiri tegak dengan pedang terhunus. Matanya tajam, penuh ketegasan.
"Kalian dari dalam benteng?" tanyanya curiga.
Nyai mengangkat tangannya perlahan, menunjukkan bahwa kami tidak bersenjata. "Kami bagian dari perlawanan. Kami ingin bergabung dengan kalian."
Lelaki itu menatap kami lama sebelum akhirnya mengangguk. "Ikut aku.
Lelaki itu melangkah lebih dulu, memberi isyarat agar kami mengikutinya. Aku dan Nyai saling bertukar pandang sejenak sebelum bergerak cepat menyusul. Suara langkah kaki kami teredam oleh tanah lembap hutan, sementara di kejauhan, sorak-sorai pertempuran masih menggema.
Setelah beberapa menit berjalan, kami tiba di sebuah celah sempit di antara dua batu besar. Lelaki itu menyingkirkan ranting-ranting kering yang menutupi jalan masuknya, lalu memberi isyarat agar kami segera masuk. Aku mengikuti Nyai, merangkak melewati celah yang gelap dan dingin. Begitu kami sampai di sisi lain, sebuah gua kecil terbentang di hadapan kami.
Di dalam gua, beberapa orang berkumpul di sekitar nyala api kecil. Wajah-wajah mereka menunjukkan kelelahan, tapi juga tekad yang kuat. Seorang pria tua dengan janggut putih menatap kami dengan mata penuh selidik.
"Siapa mereka?" tanyanya pada lelaki yang membawa kami.
"Mereka berasal dari dalam benteng," jawab lelaki itu. "Mereka ingin bergabung dengan perlawanan."
Pria tua itu mengangguk perlahan, lalu mengarahkan pandangannya padaku dan Nyai. "Apa yang kalian tahu tentang benteng? Berapa banyak penjaga yang tersisa? Dan yang paling penting, mengapa kalian ingin melawan?"
Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas yang masih memburu. "Benteng itu menyimpan banyak tahanan, orang-orang yang menolak tunduk pada mereka. Aku salah satunya. Jika kita tidak melawan sekarang, maka selamanya kita akan hidup dalam belenggu."
Nyai mengangguk setuju. "Penjaga mereka sedang kacau. Jika kita menyerang malam ini, kita punya peluang besar untuk merebut kembali kebebasan."
Pria tua itu berpikir sejenak, lalu berdiri dengan mantap. "Kalau begitu, kita harus segera bertindak. Kalian akan membantu kami menyusun rencana serangan. Malam ini, benteng itu akan menjadi milik kita."
Aku merasa dadaku bergetar, bukan karena takut, tapi karena harapan. Aku menatap Nyai, dan untuk pertama kalinya sejak pelarian kami, aku merasa kami benar-benar berada di jalan yang benar.
Malam itu, kami tidak hanya bersembunyi-kami bersiap untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Kebebasan.
Serangan dimulai tepat saat fajar menyingsing. Para pemberontak menyerbu benteng dengan senjata seadanya, memanfaatkan kelengahan penjaga yang masih lelah setelah malam penuh kekacauan. Aku berlari di antara reruntuhan, mencari jalan menuju pusat komando. Aku tahu di sanalah letak kemenangan sejati akan ditentukan.
Saat aku menerobos sebuah lorong yang dipenuhi asap dan suara dentingan senjata, tiba-tiba langkahku terhenti. Di hadapanku berdiri seorang pria dengan seragam militer yang tak asing. Matanya menyipit saat melihatku, lalu bibirnya melengkung dalam senyuman sinis.
"Sari... aku tak menyangka kita akan bertemu lagi di situasi seperti ini," ucapnya dengan nada yang begitu familier.
Tanpa ragu, aku melompat ke arahnya, mengayunkan belati dengan segenap keberanian yang kupunya. Ini bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan yang harus aku perjuangkan.
Tapi sebelum aku sempat menyerangnya, sesuatu menghantam kepalaku dari belakang. Dunia seketika berputar, pandanganku mengabur. Aku jatuh tersungkur di lantai dingin benteng, suara pertempuran menjauh dalam kesadaranku yang memudar.
Ketika aku membuka mata, tubuhku sudah terikat di sebuah ruang gelap dan lembap. Pria itu berdiri di depanku, matanya penuh kemenangan.
"Kau pikir bisa lari dari masa lalumu, Sari? Kau tetap milik kami."
Siksaan itu dimulai. Pukulan, cambukan, dan hinaan berjatuhan tanpa henti. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak berteriak. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan itu.
Hari berganti malam, malam berganti hari. Tubuhku semakin lemah, napasku tersengal. Aku tahu waktuku hampir habis, tapi aku tetap bertahan, menolak menyerah.
Hingga akhirnya, di suatu malam yang sunyi, aku terbaring di lantai dingin selku, tubuhku penuh luka, napasku tipis. Aku tersenyum samar. Aku telah berjuang, dan aku tidak menyesal.
Dalam detik-detik terakhirku, aku memejamkan mata, membayangkan dunia yang lebih baik-dunia yang bebas dari kekuasaan mereka. Dan di sanalah perjalananku berakhir.
Darahku berdesir. Aku mengenalnya. Dulu, dia adalah salah satu pejabat militer yang pernah mendapatkan kepuasan dariku saat aku masih menjadi bagian dari istana yang korup. Tapi sekarang, segalanya berbeda.
Aku menggenggam belati di tanganku erat-erat. "Dunia sudah berubah, dan aku juga."
Pria itu tertawa pelan, lalu mencabut pedangnya. "Kalau begitu, tunjukkan padaku seberapa
banyak kau telah berubah."
Tanpa ragu, aku melompat ke arahnya, mengayunkan belati dengan segenap keberanian yang kupunya. Ini bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan yang harus aku perjuangkan.
Keesokan harinya, Nyai menyusup kembali ke benteng yang telah sepi. Ia mencari Sari di setiap sudut, berharap menemukan sahabatnya dalam keadaan selamat. Namun, saat pintu sel terbuka, tubuh Nyai membeku. Di sana, di lantai dingin yang basah oleh darah, Sari terbaring tanpa nyawa.
Nyai berlutut, menggenggam tangan sahabatnya yang telah membeku. Matanya berkilat dengan amarah dan duka yang mendalam. "Kau telah berjuang, Sari. Dan aku bersumpah, perjuanganmu tidak akan sia-sia."
Editor: Difa Septiari Dinarsih


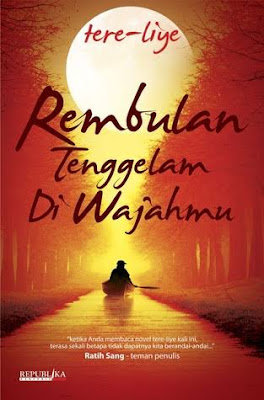
Komentar
Posting Komentar