[Ruang Karya] Cerpen
Previlisi Kota Tua
Sebentar saja, duduk dulu yang santai dan temani aku. Mohon maaf,
aku tidak bisa membuat kopi. Tangan-kaki ku sudah dimutilasi, walau aku bukan cacing planaria. Sebentar lagi kau akan mengetahui,
mengapa peluru tombak ini nyangkut di kepalaku.
Sebelumnya, manusia ini tidak mengenal “masa depan”. Aku dapat berenang kehaluan,
tak kenal mata-mata. Makin kesini, mata-mata kian semakin banyak. Tak dapat
sedikitpun aku bermeditasi. Suatu masa, aku dipaksa bergerak, otakku perlahan-lahan
di bawa hanyut dalam kedengkian, kemuraman, kemungkaran hingga ketakutan. Derup
nadi terpacu untuk terus memberi suatu kebenaran bagi dunia ini yang telah
longsor. Perbincangan masalah pohon-pohon yang menjadi sumber anti-longsor kini
perlu diterbitkan ulang. Entah, mungkin karena lapisan ozon yang semakin tipis.
Pohon itu pelan-pelan memakan sinar mentari secara berlebihan. Ulat-ulat yang
memakan dedaunan harus meniup dulu, menunggu momentum yang tepat untuk
menyantap dengan nikmat. Pun, meski ekornya kepanasan.
Suasana di kota sangat kacau. Bahkan pohon-pohon pun enggan tumbuh
disana. Aku mendapat informasi tempat buku dari buku. Tertulis kalimat indah,
“Didalam kota itu terdapat sebuah buku. Tempat itu berada dibawah burung dara.”.
Lalu, aku memikirkan dimana burung dara itu bertengger? Semuanya disini burung.
Disini bebas, tidak seperti di negara pelosok. Di pelosok, ketika
aku membuat surat undangan perkawinan anak pak lurah untuk diedarkan, kukayuh
sepedaku berputar tuk menjelajahi pelosok, aku menjadi pusat perhatian. Tatapan
para pelosok sangat sinis. Ingin sekali mereka mengambil sepedaku, tubuhku, dan
bola mataku. Di pelosok aku
melihat burung-burung diadu. Parahnya,
mereka juga mencaci
maki burung itu. Jikalau, paruhnya patah. Pun, ketika tidak patah. Sementara, paruhku berlebih-lebih dari burung itu, aku belum menemukan informasi yang berada dibuku itu.
Bayangkan saja, burung itu menerima
umpatan bahasa aneh. Ya jelas tak mengerti lah. Burung merasa kesakitan,
tubuhnya dikoyak-koyak oleh negara
‘pelosok’. Aku benci ini, jelas-lah tidak sama dengan filosofi burung.
“Kenapa burung dianggap
‘kebebasan’?”
Langkahku
seketika terhenti ketika aku menanyakan hal itu kepada perenunganku. Kukira sesuatu
itu tidak penting. Tak sadar, di depan-ku
ada orang bertopi, namun, matanya hilang satu. Aku mengajak dia bicara, namun
dia tetap diam. Seketika itu, aku sadar bahwa dia adalah patung. Selama ini aku
terlihat konyol dan idiot, burung dara yang tadi bersandar dibahuku kini turun
ke jalan, seperti para demonstran menunggu makanan. Mereka berharap biji jagung
turun kepadanya. Tak seperti di pelosok,
aku tidak menemukan hal seperti ini. Kesana-kemari aku menyusuri jalan ini dan rasanya berbeda dengan di sawah. Ketakutan burung bermula
ketika patung hidup kembali. Mereka sulit menemukan makanan ditengah ladang
yang luas.
Kubaca lagi buku itu, “Dimanakah
informasi yang akurat itu?” Dan
kau tahu? Aku
lupa menggaris bawahi-nya. Aku
mengumpat, melempar buku.
Ya,
mungkin kau berpikir. “Mengapa aku tidak lupa akan halaman dari informasi itu?” Ya,
semua karena ‘tanda baca’. Aku membeli-nya di toko mainan pada sore hari. Tepat
satu jam aku mendapatkan buku itu. Kau tidak perlu mengeluarkan kotoran yang berlebih untuk membeli
tanda baca ini. Harganya memang relatif murah. Namun, isinya sangat mahal. Oleh
karena itu, aku harap kau menyadari ini. Bukankah buku yang dicetak pada
umumnya kelihatan lebih menawan ketimbang buku usang? Ya, karena ia tidak
memiliki “Garis bawah” dan “Tanda
baca”.
Ya, ternyata informasi ini memberi
penanda sekaligus petunjuk. Kalimatnya seperti ini, “.... jikalau kau sudah
menemukan burung dara berkumpul, kau tinggal lurus saja. Namun, disinilah
tantangan nya. Kau harus lebih serius dan percaya diri tentang tanaman-tanaman
disampingmu. Tanaman terakhir berwarna putih memberi aroma mistis, lalu
disanalah kau perlu membelokkan kakimu 90 derajat ke kanan. Untuk sampai
ketujuan, tak lebih dari seratus langkah kaki, kau akan menemukan sebuah toko
bernama ‘Poeing Ampas’. Disitu tercium aroma kopi yang khas. Toko itu berada di
sudut kota, kau tinggal lurus sahaja. Kau akan menemui lampu merah, lalu belok
kiri dan sedikit lagi kau akan sampai. Namun, alangkah lebih baiknya kau
bertanya ke penjual toko mainan disana terpampang nama besar ‘Kantong Mainan’.
Penjaga disana tahu dimana tempat itu berada.” Aku merenung lagi, dan merasa
sedikit emosi. Aku mengumpat di antara kerumunan dara. Aku mengatakan “Bedebahh”.
Satu informasi
yang menurutku tak berguna, seketika
menjadi sangat berguna. Aku terlalu di mabuk ambisi untuk ke suatu tempat yang
belum pernah ku datangi. Deru jalan kota memang tak seasyik di pelosok,
disini terlalu banyak asap-asap yang mengepul.
Lalu Apakah kau
tahu? Suara
anak tertawa disini sangat jarang sekali terdengar. Terakhir aku melihatnya di
toko Poeing Ampas. Tak sekali, aku juga mendengar
sebuah suara kentut yang sangat nyaring. Kentut itu sama sekali tak menyakiti
hidung. Namun, mendengarannya sangat menyakiti gendang telingaku. Sebelum
didatangi para tentara padahal rasanya sudah hampir pecah, namun ternyata
rasanya lebih sakit mendengar sebuah kentut itu.
Ya,
ketimbang dimutilasi. Tak lama aku melihat baliho yang sangat gedhe. Dengan busana putih dan berekspresi seperti memohon untuk memilih
dia sebagai wajah kota ini. Aku tak peduli dengan orangnya. Namun, aku ketawa
tergelak-ngakak melihat kalimat seperti ini dalam baliho itu “Aku
dipilih, maka aku akan membantu kalian”. Tidak ada yang salah dengan kalimat
itu, tapi, aku menyadari suatu hal. Kenapa dalam mengajak kita harus
menggunakan kalimat yang sama? Tak bisa kah kita menggunakan “Para pencoblos
saya, adalah yang berhak memerintah dan mengkritik saya.” atau,
“Coblos
saya, kota ini akan hidup”. Kalimat seperti itu kan lebih menarik dilihat dan
menggema.
Aku kembali fokus ke jalan, perlu sedikit waktu lagi untuk aku sampai ke toko mainan
itu. Sepanjang jalan yang kulihat hanya ada pohon kering, kedai yang tutup, tembok
yang sudah ditulisi dan menarik untuk diabadikan, kucing yang sibuk menggaruk-garuk sampah, dan terakhir toko mainan itu.
Kubuka
pintu itu, perlahan-lahan aku menikmati alunan langkahku. Menariknya toko itu
ternyata bukan toko mainan. Melainkan, sebuah toko yang bersejarah. Banyak
mobil-mobil kuno yang dipajang, senapan-senapan, seragam para penjajah juga
pejuang, poster-poster, lukisan-lukisan, hingga cangkir dan sendok yang usianya
lebih tua dari diriku. Seketika aku mabuk untuk kedua kalinya, toko itu begitu
antik dan asyik untuk dikunjungi lebih dari 1 kali. Tempat ini, berada diantara
himpitan dua toko besar yang sedang berebut untuk mendapatkan pelanggan.
Berbeda dengan toko ini, kecil dan kusam dengan sebuah lumut yang hidup. Toko
ini sepertinya tidak memiliki daya tarik untuk dimasuki pelanggan. Bahkan, aku sedikit menangis karena suasana toko ini. Barang antik disini
berkilau semua, tak ada yang kusam dan berdebu. Tak lama, aku
mendapati seorang perempuan. Aku pikir dialah yang bekerja disini.
Tak
lama berselang aku bertanya, “Apakah kau tau
mengenai tempat buku yang berada di buku ini?”
Dia
hanya menatapku dengan senyuman, seolah-olah dia mengetahui sesuatu. Lalu, perlahan-perlahan dia membuka mulutnya dan menggumam
sendiri “Ah, bodoh, aku belum pernah menemukan buku ini lagi”
Aku
bingung, dan berpikir mungkin ini tempat yang salah. Tak lama, aku mendengar
sebuah kentut yang begitu nyaring lagi, bersamaan dengan suara pintu yang
terbuka dari dalam toko itu.
Masuklah
seorang paruh baya, dia berucap begini “Mengapa
kau mau masuk toko ini? Padahal disini tiada eskalator atau pengawal yang bisa membantumu.”
Aku
merenung lagi, dan lagi. Hingga seorang paruh baya itu menanyakan kepada
perempuan itu. Aku sendiri tak terlalu mendengarkan bisikan mereka. Aku
terkaget, sebuah tepukan yang tepat di bahu ku membuatku tersadar.
Paruh
baya itu berkata lagi “Mengapa kau
merenung anak muda? Padahal aku
bertanya untuk memastikan kau bukan dari kalangan para tentara”
Aku
terpaku, pasalnya aku pernah melihat keburukan para tentara itu. aku mengucapkan
dengan sedikit rasa gugup “Maaf mbah, saya
dari kalangan anak remaja. Bukan dari orang dewasa, apalagi para tentara.”
Seorang
paruh baya itu tertawa lalu mengatakan “Hahaha,
kau mempunyai trauma terhadap para tentara kan?”
Aku
bertanya-tanya dalam hati, apakah dia dukun? Atau informasi buku ini salah? Paruh baya itu
mengatakan begini “Kalau kau malu untuk mengatakan tujuanmu sebaiknya tidak
usah kesini nak. Ini toko sudah tidak memiliki nilai berharga lagi. Oh iya, aku
tau buku yang kau pegang itu. Pengarangnya adalah anakku, dan dia telah
disembunyikan oleh para tentara. Jangan kau bertanya apakah aku
sedih atau tidak? Tentu, aku akan menjawab tidak. Karena aku adalah tentara
juga. Aku sudah diberhentikan secara tidak layak. Sebenarnya buku itu adalah
alasan mengapa aku berhenti nak. Kalau kau tau, buku itu secara tidak langsung
mengungkapkan perilaku busuk para tentara. Tentunya acuannya adalah diriku
sendiri, nak. Aku memberi dongeng-dongeng terhadap anakku.”. Nadiku terkejut ketika mendengar kabar ini.
Paruh baya kemudian bercerita lagi,
“Mengapa
dalam buku itu penerbitnya sangat tidak terkenal atau bahkan tidak ada orang
yang mengetahuinya. Bahkan pengarang buku itu tidak ada yang mengenal dirinya.
Tak ada yang berani menerbitkan buku ini kecuali perempuan yang menjaga toko
tadi. Dia belajar mesin ketik dari ketidak-tahuan. Dia bekerja sangat keras
agar buku ini terbit. Tepat setelah buku ini dijual kepada para penjual buku
yang lapaknya mendapati banyak pelanggan. Buku ini, laris manis. Namun, sang
pengarang mendapati kesalahan, ketika dia mengakui bahwa dialah yang menulis
buku itu saat aku berkumpul dengan para tentara. Muka para tentara seketika
sinis terhadap anakku. Ketika aku berpatroli di daerah taman burung dara itu,
aku telah mendapati anakku dimutilasi, nak. Tubuhnya berlumuran darah dan
tubuhnya terpisah dengan tulang belulang nya. Aku sangat mengingat hal ini,
para tentara biadab itu menulis dengan tubuh dan tulang belulang anak saya.
Kalimatnya seperti ini, nak “Kau Salah” susunan itu sangat rapi. Menurutku
tidak, nak. Seharusnya kalimat itu begini “Aku Benar”. Aku
mengangkat anggota tubuh anakku. Saat itu Aku tak
kuat nak, urat-otot ku lemas. Ya, begitulah nak. Kau harus hati-hati terhadap
negeri ini, nak. Kalau tak ingin seperti anak saya.”
Diakhir
kalimat dia berucap seperti ini “Kau
masuklah kebelakang, keluarlah dari jendela. Kau harus ke tempat Poeing Ampas,
nak. Lalu mengabari bahwasanya aku telah bernasib seperti anakku.”
Aku
menaiki jendela, menutup lalu pergi. Terdengar oleh kuping kananku suara revolver yang sangat nyaring. Kau tahu
nadanya seperti apa? Tembakan pertama bernada “dar”, kedua “der”,
ketiga dentuman bom dengan bunyi “Mampus kau biadab”. Hal itu, lebih membuatku
kaget ketimbang suara kentut yang berseliwingan. Ternyata aku telah dibuat
mabuk untuk ketiga kalinya.
Aku
baru menyadari sesuatu dalam buku itu. Terdapat pada prolog, “Kau
akan mendengar suara dentuman keras,
saat itu larilah atau kau akan dicurigai”. Berlari sekuat tenaga adalah
alasanku untuk terus hidup. Nahasnya, toko
selanjutnya yang aku ingin datangi telah diamankan oleh para tentara. Sedikit
tenaga, meski terengah-engah aku tetap menenangkan diri. Namun, sialnya, mata-mata
telah menghantui gerak-gerikku sejak berada di taman. Aku telah ketahuan,
dengan cepat aku menaiki angkutan umum untuk kembali ke pelosok.
Sebelum terlambat.
Aku berpikir bahwa seorang mata-mata
akan menemukan identitas saya dengan cepat. Aku tak mau kalah licik dengan mata-mata
itu. Lari merupakan solusi yang paling menjawab waktu itu. Aku tak bisa lagi
meditasi diruangan ini. Ruangan ku terlalu jauh untuk ke kota.
Tak
terjawab aku akan bermeditasi dimana, akankah
gunung? Atau menumbuhkan sayap sama seperti burung? Ah, entahlah. Selama
menaiki angkutan umum aku mencari tempat persinggahan. Diantara mereka tidak ada satupun yang mau
menerimaku untuk disinggahi tempatnya. Aku membaca koran seraya menunggu
angkutan umum lain tiba.
Sebuah
kalimat dengan bunyi “Hutan adalah kehidupan manusia” membuatku memantapkan pilihan. Seketika itu juga aku
berpikir untuk bersinggah diri di hutan.
Tentunya, yang tidak terikat dengan vegetasi manusia. Aku mencari hutan
belantara yang memiliki suatu tebing yang pas untuk ditinggali. Di malam
hari, aku bersandar pada lentera yang kubeli kemarin sore untuk meneruskan
aktivitas menjelajah ini. Aku tak takut sedikitpun, pada hantu-hantu hutan. Aku
lebih takut terhadap nafas ku yang berhenti akibat para tentara membunuhku.
Terheran-heran aku tak memiliki satupun rasa payah dalam benak pikiranku.
Perjalananku memang sedikit tersungkur kantuk yang tak mungkin usai. Namun, aku
tak memikirkan kantuk ku yang berlebih ini. Selama perjalanan aku menyusuri
hutan-hutan belantara ini, tak jarang aku mendapati rantai makanan yang telah
digambarkan dalam pelajaran anak-anak kecil.
Udara hutan lebih segar dan
menyegarkan pada mata ini. Jikalau, aku mengembara di kota mungkin aku sudah
mati. Disuguhkan dengan aroma makanan kelas atas, kopi, dan hidangan kaum
menengah bawah karena melihat tubuhku seperti orang hampir bermain dadu dengan
maut. Tentunya bukan dengan para tentara. Berhari-hari aku mencari tempat yang sesuai
dengan keinganku. Ya! Hutan yang memiliki suatu tebing. Tak pernah kutemui
tempat itu.
Ini menjadi titik menjelajahi hutan untuk beristirahat, dipinggiran danau yang dikelilingi tembok-tembok bebatuan. Hanya membutuhkan satu cara, untuk mendapati tempat ini dengan menggunakan otot-otot kaki. Ditempat ini aku merasakan suatu tempat yang sangat nikmat. Aku mematahkan keidealanku, tempat yang pas tak menjadi jawaban bahwa kau akan mendapatinya. Hidupku sangat bahagia disini, kicauan burung-burung terdengar tegas dan keras, sapi-sapi disini merasakan kenikmatan rumput yang segar. Pun, ikan-ikan nya menjadi ciri khas untuk hiasan danau ini. Tempat ini merupakan titik kumpul mata air yang nantinya bergilir ke sungai-sungai dibawahnya.
Jangan kau bertanya bagaimana aku hidup di tempat ini. Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh disini lebih bermakna hidupnya. Dia liar, bergoyang, dan tentunya alam sangat menyukai hal itu. Kuhitung untuk ketempat ini membutuhkan sekitar satu pekan lebih. Disini tak ada para tentara. Pun, hutan tidak dimiliki oleh siapapun, aku menyukainya seperti puisi. Ah, berbicara tentang puisi. Aku sudah lama tak membuatnya. Kucoba menulis perlahan-lahan pada tanah yang direstui oleh alam.
Tengah hutan tanpa nyamuk, lalat,
dan semut
Tanpa jejak
digital, hidupku,
Tidurku, semakin
Sehat
Euforia!
Hidup tanpa suara
kentut
Adalah kebebasan
Baliho, bambu
runcing, juga
Suara
Hutan tidak
mengenal setan
Hutan tidak
mengenal tentara
Hutan tidak
mengenal mitos
Hutan mengenal
alam
Alam mengenal
hutan
Mitos adalah
hantu, pun
Garuda.
Tiga puluh tujuh hari aku hidup
disini. Pun, umurku. Siang menjelang sore ketakutanku muncul. Meditasiku telah
diketahui oleh para tentara, mereka berjumlah 34 orang. Para tentara itu tidak
terlatih. Ternyata! Mereka membutuhkan mesin-mesin untuk mencari diriku. Entah
apa yang dicari dalam diriku. Aku masih bertanya-tanya, aku tidak memiliki uang
sepeser pun. Aku hanya punya alam, aku hanya punya kesadaran, dan aku
hanya punya ketakutan. Tak lebih dari itu, tapi para tentara biadab itu
menganggap aku memiliki segalanya. Mereka rela menganggap aku ‘tuhan’.
Mereka tak rela terhadap istri, anak dan negara. Aku tak memiliki siapapun. Aku
hanya punya alam. Para tentara itu mengepung, muka mereka seperti babi-babi
pemakan kotoran. Aku yakin, mereka tak mempunyai ‘tanda
baca’.
Otak mereka kosong, hati para tentara itu telah ditelanjangi. Kaki mereka telah
diikat.
Aku, mencomot sebuah buku. Alamatnya berada diluar
garis katulistiwa, dengan deru kencang aku berlari, tersandung demi sebuah
buku. Perlahan-lahan, kubawa buku itu dengan setaat mungkin. Namun, saat para
tentara datang untuk merampas, memaksa, lalu meninju, menendang, dan berakhir
menempatkan tendangan gacor ke mukaku. Sontak mataku terkena pucuk ranting, perlahan-lahan mereka membuka
lemari sejarahku. Mereka mengambil sumbangsih-sumbangsih beberapa naskah di
lemari panjang berbentuk segitiga dengan kayu sedikit lusuh. Diambil, dirampas, dan dibakar.
Dimana
aku mendapatkan sebuah kenikmatan, jikalau tidak di alam? Aku dan alam adalah
satu keluarga. Aku merusak, alam juga merusak. Aku menjaga, alam juga menjaga.
Tapi, dalam sebuah hutan ini hanya satu pohon yang tidak pernah aku urusi.
Mengapa ya? Mungkin karena itulah alasan para
tentara datang ke hutan itu. Padahal, hutan itu tidak memiliki nilai eksotis
sedikitpun, tapi sayangnya sampah dibakar
dipohon itu. Kau tahu, di pojok hutan itu ada pohon dengan bentuk perut kita,
bolong tengah. Disanalah, para tentara membakar sisa-sisa meditasiku, selama
tiga puluh tujuh hari. Anehnya, pohon itu tak terbakar, Ia memiliki sebuah
volume angin yang pas untuk melaksanakan proses pembakaran. Buku-buku pun
dibuang disana. Aku merasa kasihan terhadap buku saja, kalau yang lain, sudah
bakar saja.
Mataku
sayu diterjang peluru tombak. Otak kiri-belakangku rusak. Bak DVD bunyinya agak
konslet, namun tak pernah jatuh ke toilet. Selintas cahaya jatuh menerangi
lampu rumah. Disana terdapat keaneahan-keanehan. Muka-muka bapak menakutkan,
kakak telah menjadi sapi seutuhnya untuk disembelih. Dan, aku. Tidak mempunyai
apa-apa kecuali satu mata kiri yang terkena peluru tombak ini. Kuping? Aman,
sehat wal afiat. Mulut? Wah, kurang sehat, soalnya nyerocos melulu!. Nahasnya, kaki dan
tangan telah dimutilasi, menjadi objek uji coba. Kalau tidak salah aku
mendengar umpatan-umpatan para tentara kalimatnya begini “Demi penebusan tiga
juta”. Kalau tidak salah disana juga terdapat keringat bau-bau kotoran yang menyengat. Seperti, kalau dipikir, nah sepertinya aku adalah debtcollector.
Oh, bukan ya. Ya, aku ingat, seperti emm. Hei, sebentar, ada sinar mentari di
kanan kupingmu. Boleh ya aku ambil sebentar untuk menapaki keindahan bola mata
ku ini ucap para tentara.
Pada
saat itulah, aku mencomot buku itu kembali. Aku katakan pada tentara itu “Aku
tidak mencomot, aku ingin mengoleksi saja. Mengapa aku tidak boleh mengoleksi suatu buku?
Peluru
tombak menyeringai membuat gambar senyuman di mata kiriku, crot bunyinya.
Aku tidak diam, aku berlari mengejar buku itu hampir sahaja terkena bara api.
Namun, kedua kaki ku jatuh dicium batu, dan tanganku menjadi sapu lantai pembersih para tentara. Lalu, aku diseret dan dicekokin peluru tombak, dari
mata hingga otak kiri. Sampai, aku tidak
diamankan. Aku menerima pukulan yang memukau. Silau
seperti berada di sirkus komedi.
Tendangan
yang sangat semangat, menghangat, merapat dalam tembok batu, dan berakhir
mutilasi. Jangan kau bertanya tentang perenunganku. Aku merenungkan bagaimana
tubuhku beregenerasi lagi. Aku merindukan apabila otak,
kuping kanan, mata kiri, kaki, tangan, jantung, paru-paru, nadi tidak sejalan.
“Aku sedang berada diluar ambang kesadaran”.
Sekali
lagi aku mengucapkan “Aku tidak mencomot buku, aku hanya mengoleksi saja”. Kemudian, peluru tombak itu menancap dengan indahnya. Mengukir tubuhku.
Para tentara itu hanya tau merusak mata, kuping, hidung, mulut, kaki, dan
tangan saja. Mereka tidak mengetahui cara merusak pikiran dan hati.
Sebelum
kuping saya menjadi datar aku mendengar kali terakhirnya “Penebusan tiga juta” Tepat!
Itu adalah harga dari meditasiku ditengah hutan ini. Karena
senyumanku, mereka ketakutan dan membuang ku ke danau itu. Aku takjub,
ikan-ikan tak memakan bangkai diriku dan sapi-sapi sudah tidak ingin makan
rumput lagi. Burung sudah muak berada ditempat seperti ini. Semua karena
tindakan para tentara bermesin itu. Sudah, semuanya hangus dibakar.
Editor: Lulus Anggun dan
Yohanna Gabriella


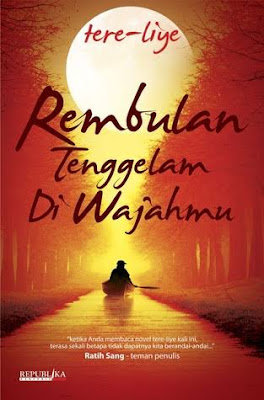
Komentar
Posting Komentar